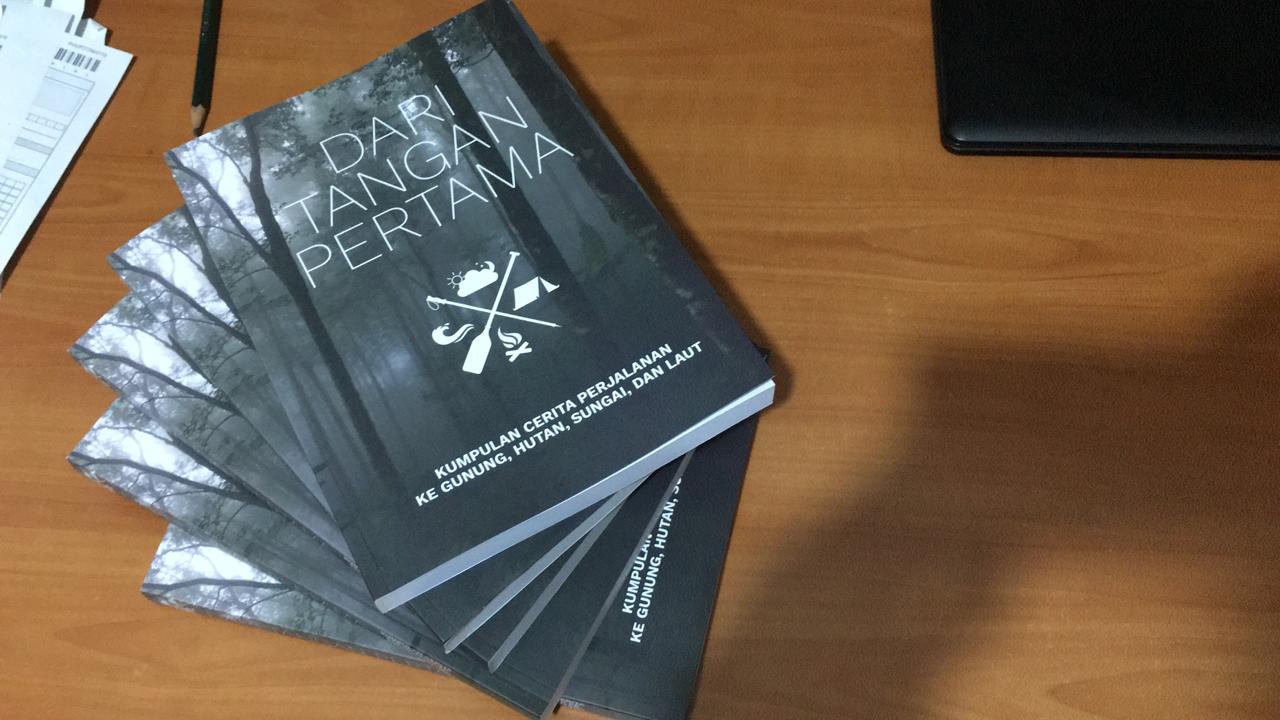PAGI itu mendung. Rintik hujan menyapa Jakarta di awal 2018. Membuat sang fajar malu menampakkan diri.
Meski demikian, denyut kehidupan ibu kota tetap berjalan. Senin pagi memang waktunya warga memulai aktivitas. Namun tidak seperti kami yang mencoba menjajal arus Ciliwung.
Bersama kawan-kawan dari komunitas Ciliwung di Srengseng Sawah, kami berangkat ke Jembatan Panus, Depok.
Persiapan sudah dilakukan sejak semalam. Perahu dicek, alat perlengkapan diri tak lupa. Helm, dayung, pelampung. ‘Dry bag’ juga wajib disiapkan, agar barang bawaan, terutama elektronik aman sentosa.
Kayak dan kano di-‘packing’ di atas mobil. Sementara beberapa perahu karet diambil dengan mobil bak dari Depok. Tak lupa kami isi perut dengan penganan khas ibukota, nasi uduk plus gorengan.
Sebentar, serius nih main di Ciliwung? Yes, sebagai orang awam, pertanyaan itu juga saya rasakan ketika seorang kawan mengunggah ‘Whatsapp Story’, ‘Bersiap Main Air di Ciliwung’.
“Bro, bukannya Ciliwung bau, kotor, sampah? Apalagi sekarang musim hujan. Gak takut banjir?” tanyaku.
Doi dengan santai jawab, “Kalau mau ikut dateng aja. Tinggal duduk manis saja. Semua disiapkan”.
Ajegile, pertanyaan gak terjawab. Malah ngajak aja. Mau gak mau saya harus datang mencari tahu, ada apa di Ciliwung. Sejurus, buat menjawab tantangan itu.

Kembali ke persiapan tim, kami lalu tancap gas. Sekira setengah jam kami sampai, setelah melalui lalu lintas Margonda yang lumayan padat.
Sampai di Panus, jembatan yang monumental itu, kami cek ulang alat, sembari menunggu datangnya ‘riverboat’ dari Depok.
Saya coba orientasi medan. Melihat-lihat kondisi jembatan ini. Ada pos pemantau air Depok yang biasa memberikan informasi ‘debit’ air. Sebagai warning banjir kiriman dari Bogor.
Rasa penasaran terhadap jembatan ini membuat saya ‘googling’. Ternyata Jembatan Panus dibangun oleh insinyur yang juga masih keturunan Depok Lama, Andre Laurens, pada tahun 1917. Lama juga nih jembatan.
Nama Panus tentunya bukan nama resmi jembatan ini. Panus merujuk pada seseorang bernama Stevanus Leander, warga Depok Lama yang tinggal di sisi timur jembatan, dan bertugas merawat jembatan ini.
Konon, sampai sekarang keluarga dan keturunan Stevanus Leander masih tinggal di sekitar jembatan ini.
Sebelum dibangun jembatan ini, perjalanan darat dari Depok ke Buitenzorg (Bogor), harus disela memakai rakit (yang disebut Eretan dalam bahasa lokal), menyeberangi Sungai Ciliwung.
Untuk mencapai bibir sungai, saya harus meniti jalan curam. Hati-hati sekali, agar tidak jatuh. Ya jalannya licin. Jika tidak ya wasallam. Benar saja, brakkk! Seorang kawan terpeleset, jadi korban.
Saya mencoba melipir pinggiran kali lebih jauh. Sampah memang jadi tuan rumah di kali ini. Kali purba yang oleh sementara kalangan dianggap sumber ketenangan, kini jadi korban rakus manusia.

Setelah menunggu, akhirnya semua siap. Satu per satu turun ke perahu. Instruktur mem-‘briefing’ standar operasi. Bagaimana memdayung, menjaga kekompakan dan prosedur keamanan ketika terjadi kecelakaan. Ini kegiatan beresiko bung, jangan lalai! Yang jua tak lupa dilakukan adalah pemanasan.
‘Welcome to the river’. Medan air dengan riam-riam kecil menyambut tim yang masih bersemangat. Debit air lumayan tinggi, membuat perahu melaju cukup deras. Guncangan demi guncangan, membawa tawa dan sensasi tersendiri.
Di kejauhan, pohon beton berdiri kokoh. Kemungkinan, apartemen yang ada di kawasan Margonda. Ia pamer badan, seakan paling angkuh di antara yang lain, mentang-mentang besar.
Tapi, ini juga menjadi sensasi tersendiri. Kalau di tempat lain, kalian ‘rafting’ dikelilingi hijau asri, di Ciliwung kalian berolahraga arus deras dengan latar gedung pencakar langit.
Bukan cuma itu, sampah jadi hal lumrah di sini. Di beberapa titik, sampah mencapai dahan tinggi, seperti tupai yang memanjat dengan fasihnya.
Hal lain yang cuma memancing perhatian saya, tawa riang anak-anak saat kami melewati beberapa spot. Di Jembatan Juanda misal, sekelompok anak yang masih berseragam berteriak. Senang, gembira, jenaka seperti melihat kapal terbang dan meneriaki, “Kapal, minta duit”.
Tapi kami sadar, mereka generasi penerus yang harus diberi pemahaman. Sungai ini bagian peradaban. Kalian harus menjaganya. Jangan kotori, jangan sakiti. Sebab jika alam mengamuk, manusia yang merugi.
Banjir karena sampah, longsor karena tanah gerak. Kami membalas teriakan mereka, “Besok ajak teman-teman kalian, sekolah kalian turun ke sini, ke Ciliwung. Jangan buang sampah ke kali”.
Tak berapa lama, sampailah ke titik ekstrem perjalanan. Riam Kebo Gerang, warga menyebut demikian. Beberapa ratus meter sebelumnya, ‘skipper’ kami sudah mengingatkan, awas Kebo Gerang. Dayung lebih cepat supaya tidak kegulung.
Adrenalin mulai terpacu merasakan detik-detik masuk ke riam ini. Guncangan kami rasakan. Hingga akhirnya mereda. Banyak perahu lain, karena terlalu pinggir, akhirnya menghantam batu tepian kali, meski tak sampai terbalik.

Sayang, sensasi Kebo Gerang cuma bisa dirasakan saat musim penghujan. Kalau kemarau, bahkan ada beberapa kawan yang mengangkat perahu mereka. Mentok batu kanan kiri.
Selesai melewati hadangan Kebo Gerang, rombongan menepi di sebuah area yang lumayan lapang, masih dekat riam itu.
“Ayolah, ngopi apa ngopi,” seru salah satu rekan.
Maka, kompor lapangan pun diturunkan. Masak air, aduk, lalu seruputlah kopi si hitam manis. Jangan lupa dengan dorongan. Ada pisang goreng, ada pula lontong. Lapar apa doyan bro. Pokoknya ajib deh.
Selesai ngopi kita lanjut ngarung lagi. Arus semakin tenang, sampai kita selesai di garis Saung Bambon, Srengseng Sawah. Dengan elu-elu warga menyambut kami.
“Kayak pahlawan aja kita bro disambut,” celetuk seorang teman.
‘Experience’ belum selesai gan. Masih ada nasi liwet yang menunggu untuk dihajar. Gak pake lama, sikat! Di sela makan saya sempat berujar ke beberapa kawan, menarik jika susur sungai ini dijadikan model pariwisata. Tentu dengan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dari awal sampai akhir memberikan sensasi tersendiri. Jika pengelolaannya baik, bukan tidak mungkin Ciliwung menjadi destinasi pariwisata alternatif perkotaan. Memang pekerjaan rumah yang panjang. Tapi bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan.
Lagi-lagi saya mencoba mengambil contoh kesuksesan Desa Wisata Nglanggeran di Gunung Kidul Yogyakarta atau Desa Wisata Gubuklakah di Malang. Kedua desa itu bisa bangkit dari keterpurukan menjadi sejahtera dengan pendekatan pariwisata.
Dulu orang kenal Gunung Kidul sebagai sentra kemiskinan, bahkan cuma bisa makan gaplek, walang, kepompong. Tapi sekarang, siapa tak kenal kawasan yang masuk karst Gunung Sewu.

Pendapatan Asli Daerah meningkat tajam, untuk Nglanggeran sendiri berhasil mengelola aset Rp1,2 miliar. Sumber valid dari kawan pengelola.
Sementara Desa Wisata Gubukklakah, mereka akhirnya bisa menarik tamu yang biasanya hanya melewati desa mereka untuk lanjut ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Alhasil, setiap akhir pekan desa yang terkenal dengan ladang apel ini selalu penuh oleh wisatawan.
Setelah sehari yang menyenangkan itu, saya selalu bercerita ke banyak kawan soal Ciliwung. Bahkan ke narasumber saya. Sekedar informasi, sehari-hari saya menjadi jurnalis di Kedai Pena.
Bagaimana responnya? Beragam, ada yang tertarik, heran, bahkan mencibir. Di antaranya adalah Biem Benyamin, tokoh Betawi yang juga anak dari legenda Benyamin Sueb. Ia sangat antusias dengan konsep pariwisata Ciliwung.
Biem sendiri sempat berkunjung untuk melihat potensi Sungai Ciliwung sebagai sebuah destinasi wisata. Biem merasakan sensasi ngopi di pinggiran sungai Ciliwung.
Ia bercerita soal kenangannya semasa kecil. Biem menceritakan soal sosok ayahnya, yang gemar sekali bermain air di sungai.
“Waktu saya kecil. Setiap keluar kota dan melihat sungai dengan air jernih, pasti Babeh (Biem Benyamin) minta berhenti untuk nyebur, mandi,” ujar Biem.
Dengan kondisi demikian, lanjut Biem, dirinya pun mengaku rindu agar Sungai Ciliwung bisa digunakan seperti itu.
Biem pun berharap agar Sungai Ciliwung yang berada di Srengseng Sawah ini bisa dijadikan destinasi wisata di DKI Jakarta.
“Misalnya disini nanti ada tempat makanan, tempat bersih-bersih serta mandi. Bisa dibangun jembatan antara sisi-sisi Ciliwung, kemudian ‘flying fox’. Dari situ nanti kita tinggal promosikan di sosial media,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sementara, owner produsen peralatan alam bebas Avtech, Yudhi Kurniawan yakin sektor pariwisata bisa tumbuh dengan baik di Ciliwung. Asalkan dibarengi komitmen serius antar ‘stakeholder’, termasuk warga, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain-lain.
Ia pun berharap, semua elemen membuat masterplan pengembangan pariwisata yang mumpuni. Tentu dengan pelibatan masyarakat di sekitar Ciliwung.
“Jangan sampai masyarakat cuma jadi penonton. Makanya harus ada ‘master plan’ yang jelas, daerah mana diperuntukan untuk apa,” sambungnya.
Bukan hanya itu, ia pun meminta adanya koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Sebab, Ciliwung dilintasi dua provinsi, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Kalau koordinasi di tingkat pemerintah, kementerian atau lembaga terkait tidak rampung, mustahil pengembangan wisata Ciliwung akan berjalan baik.
Soal pengembangan pariwisata, banyak model pengembangan yang bisa dilakukan. Selain olahraga air, pembuatan spot-spot selfie mutlak harus dibangun.
Sebab, Yudhi melanjutkan, semakin banyak orang menggunggah foto, membuat Ciliwung viral. Setelah itu, dapat dipastikan wisatawan berbondong-bondong mendatangi Ciliwung.
“Spotnya gak perlu mahal, bisa dengan menjejerkan ‘hammock’ bertingkat di antara dua pohon. Atau sepeda di atas kali dengan bantuan ‘sling’. Pokoknya yang ‘instragramabble’, biar orang bisa ‘selfie’,” tandas penggiat pramuka ini.
Senada, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, TB Haeru Rahayu berujar konsep wisata Ciliwung akan berkembang dengan tiga syarat.
“Pertama ialah atraksinya. Tapi, aktraksinya jangan hanya dicontohin orang mandi saja. Mestinya bisa hal lain. Di sini kan lucu, pohon saja ada bajunya (sampah),” kelakar dia.

Tidak hanya itu, lanjut TB, yang kedua adalah aksesibilitas. Khusus, di wilayah DKI Jakarta sendiri hingga saat ini masih cukup terjangkau dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan tempat wisata.
“Kalau aksesibilitas untuk di DKI Jakarta dan Jabar sih oke. Walaupun memang masih macet,” imbuh TB.
Terakhir, kata TB, ialah soal ‘amenity’ atau fasilitas yang dimana bukan hanya persoalan hotel atau tempat menginap saja. Namun, juga keterlibatan masyarakat untuk bahu-membahu membangun tempat wisata tersebut lewat ‘homestay’.
“Ini adalah bagaimana mengubah ‘mindset’ masyarakat,” pungkas TB.
Ya, perjuangan baru saja dimulai. Mimpi menjadikan Ciliwung destinasi wisata perkotaan harus dijaga. Jangan sampai asa itu hilang karena kita tidak mampu merawat. Semoga Tuhan selalu bersama orang-orang yang berani bermimpi dan menggapai mimpi itu. Panjang umur perjuangan. Masyarakat sejahtera, konservasi terjaga, pariwisata membahana. [***]
Oleh Ari Purwanto, Jurnalis di Kedai Pena. Tulisan ini juga dipublikasi dalam buku ‘Dari Tangan Pertama’ yang dirilis dalam acara Outfest, bulan Agustus 2019